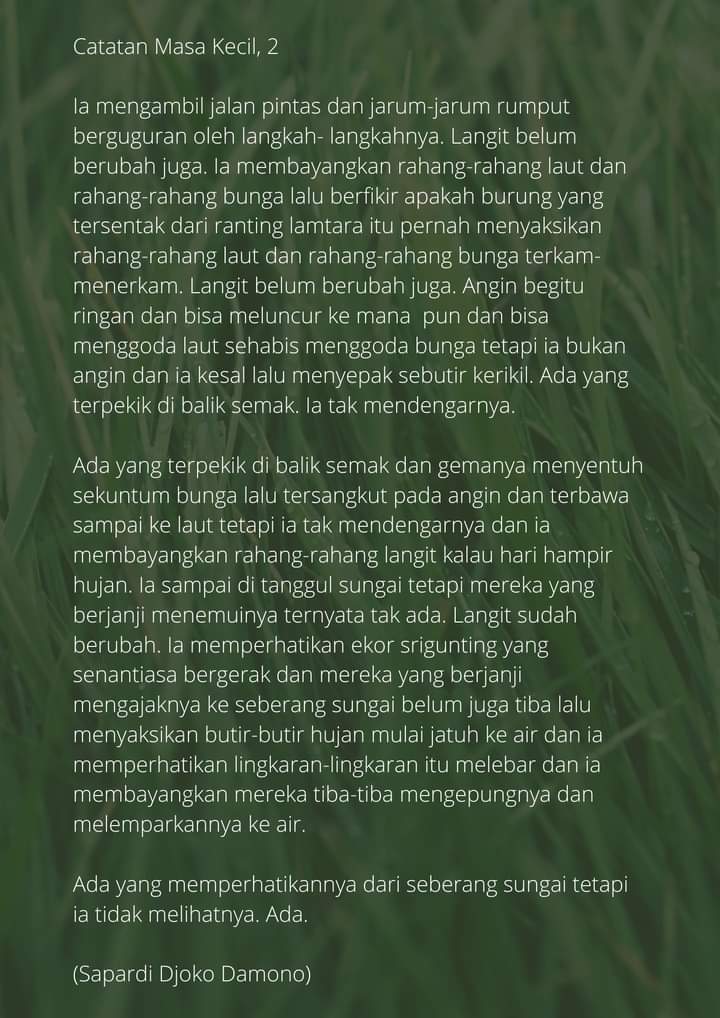
Sesuatu, yang maknanya berhimpit dengan yang tak masuk akal, yang juga terpendam di bawah jerit dan sorak masa kecil, sangat sering hidup kembali dalam puisi saya.
Dalam beberapa sajak yang saya tulis tahun 1971, keinginan saya untuk menyampaikan sesuatu itu tersirat dari judul sajak; namun, sebenarya saya benar-benar mendapatkan keasyikan yang luar biasa ketika menulis catatan-catatan tersebut.
CATATAN MASA KECIL, 2
Ia mengambil jalan lintas dan jarum-jarum rumput berguguran …
Saya sungguh-sungguh asyik bemain kata-kata sehingga tercipta “rahang-rahang laut”, “rahang-rahang bunga”, dan “rahang-rahang langit”, dan kagum menyaksikan “rahang-rahang laut dan rahang-rahang bunga terkam-menerkam”.
Saya senang menyaksikan “angin yang begitu ringan dan bisa meluncur ke mana pun dan bisa menggoda bunga sehabis menggoda laut”.
Dan saya menjadi terkejut ketika “ada yang terpekik di balik semak” ketika saya “menyepak kerikil”.
Saya terlibat sepenuhnya dalam permainan kata itu, sampai pada saat ketika menyadari bahwa rasanya ada sesuatu yang muncul (kembali) dalam dunia rekaan saya itu.
Pada saat semacam itulah saya biasanya berhenti menulis; proses penciptaan pun selesai.
Dalam sajak itu saya membayangkan diri saya berjalan sendiri lewat jalan setapak menuju sungai di bawah “rahang-rahang langit” untuk memenuhi janji dengan beberapa orang.
Sesampai di tepi sungai, “mereka” ternyata tak ada; hari pun hujan, dan serasa ada yang memperhatikan dari seberang sungai, sementara terbayang “mereka” mengepung dan melemparkan saya ke sungai.
Rangkaian peristiwa itu seperti pernah saya alami di masa kecil namun tidak pernah saya sadari sebelumnya sejak itu selesai ditulis.
Oleh karena itu, pengalaman tersebut bukan merupakan sesuatu yang sudah ada atau sudah jadi sebelum sajak itu mulai ditulis;
dengan kata lain, ia bukan merupakan tujuan penulisan sajak tersebut.
Tetapi kenyataan itu tidak membuktikan bahwa penulisan sajak tersebut berawal tanpa maksud apa pun.
Sajak itu merupakan salah satu dari serangkaian sajak yang berjudul “Catatan Masa Kecil”, dan tentunya ditulis dengan semacam niat untuk mengungkapkan pengalaman masa kecil—atau dengan istilah yang saya pakai sebelumnya: yang tak masuk akal.
Beberapa kata yang saya pilih untuk sajak itu seperti “laut”, “langit”, dan “bunga” tentu boleh diterima sebagai lambang;
ini wajar saja, sebab saya, seperti halnya kebanyakan penyair, mempergunakan perbandingan untuk mengetatkan bahasa.
Tetapi dari segi pengalaman yang ada dalam diri saya, kata-kata itu sekaligus juga bermakna sama dengan yang diacunya.
Tentu saja pembaca boleh menafsirkan “langit” dan “sungai” dalam sajak tersebut sebagai lambang-lambang untuk akhirat dan kehidupan,
tetapi bagi saya kata-kata itu sekaligus berarti langit dan sungai benar-benar.
Kemungkinan besar segala hal dalam masa kecil saya diam-diam telah menjelma menjadi lambang-lambang; atau mungkin juga di masa kecil, lambang-lambang telah menjelma dalam hidup sehari-hari sebagai hal-hal yang nyata—dan karena itu tidak masuk akal.
(Sapardi Djoko Damono)